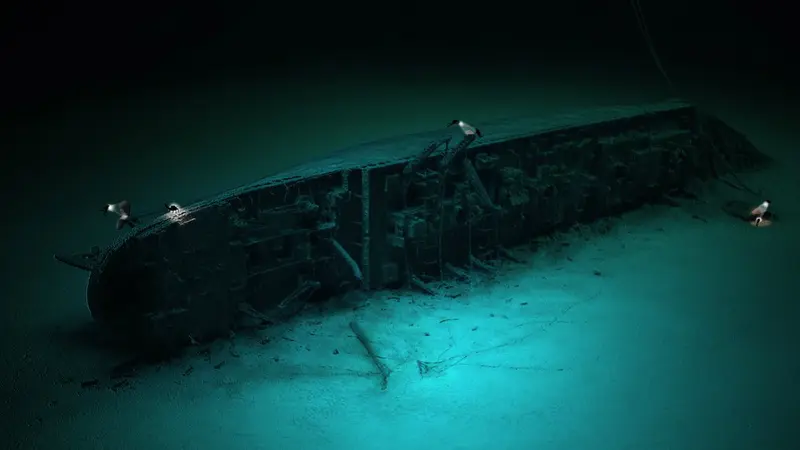Di tengah hamparan sawah yang hijau di Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, berdirilah sebuah desa yang menyimpan kisah panjang tentang sejarah, keyakinan, dan tradisi. Desa itu bernama Sonoageng. Bagi masyarakat setempat, nama Sonoageng tidak sekadar sebutan administratif, melainkan simbol dari perjalanan spiritual yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di antara cerita yang paling melekat di hati warga adalah legenda tentang Mbah Sa’id Anom, tokoh yang diyakini sebagai pembuka wilayah sekaligus penjaga keseimbangan desa hingga kini.
Kisah ini bermula dari masa-masa penuh gejolak di penghujung abad ke-18. Sekitar tahun 1796, ketika Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwana II, terjadi peperangan besar melawan penguasa Solo, Mas Sa’id. Pertempuran itu dimenangkan oleh pihak Yogyakarta, dan Mas Sa’id akhirnya diasingkan ke negeri jauh yang dikenal sebagai Sailon, atau sekarang disebut Sri Lanka. Namun, sejarah mencatat bahwa salah satu keturunan Mas Sa’id, yaitu Raden Sa’id Anom, berhasil meloloskan diri bersama beberapa kerabatnya menuju wilayah timur Pulau Jawa.
Perjalanan panjang itu membawa mereka ke sebuah tempat yang masih berupa hutan rimbun dan sunyi. Di sanalah Raden Sa’id Anom memutuskan untuk menetap. Ia menata kehidupan baru, membuka lahan pertanian, dan mengajarkan nilai-nilai spiritual kepada warga yang mulai berdatangan. Seiring waktu, ia lebih dikenal sebagai Mbah Sa’id Anom, seorang pendeta dan guru bijak yang dihormati oleh masyarakat sekitar. Setelah wafat, makamnya dijaga dengan penuh hormat di tengah desa, dan hingga kini menjadi pusat kegiatan keagamaan serta budaya masyarakat Sonoageng.
Salah satu tradisi yang masih lestari hingga saat ini adalah nyadran, sebuah ritual warisan leluhur yang dilakukan untuk mengenang jasa dan mendoakan arwah para pendahulu, khususnya Mbah Sa’id Anom. Kata nyadran sendiri berasal dari bahasa Sanskerta sraddha, yang berarti keyakinan. Bagi masyarakat Jawa, nyadran adalah bentuk penghormatan kepada mereka yang telah tiada sekaligus wujud syukur atas kehidupan yang masih dijalani.
Setiap tahun, pada hari Jumat Pahing setelah panen kedua atau yang disebut walik’an, seluruh warga Desa Sonoageng berkumpul di balai desa. Dari tempat itu, mereka melakukan kirab budaya menuju makam Mbah Sa’id Anom yang berjarak sekitar lima ratus meter. Barisan warga berjalan dengan tertib sambil membawa tumpeng dan hasil bumi sebagai simbol rasa syukur kepada Tuhan atas keberkahan yang diterima. Suasana menjadi khidmat sekaligus hangat; aroma nasi tumpeng yang gurih bercampur dengan wangi bunga dan dupa yang dibawa untuk berdoa.
Bagi masyarakat Sonoageng, tumpeng bukan sekadar hidangan, melainkan lambang doa dan pengharapan. Bentuknya yang mengerucut ke atas melambangkan hubungan antara manusia dan Sang Pencipta. Setiap lapisan nasi dan lauk-pauk yang menyertainya menyimpan makna: kesyukuran, rezeki, dan keseimbangan hidup. Saat tumpeng dibagikan setelah doa bersama, masyarakat saling bertukar senyum, memperkuat rasa persaudaraan dan kebersamaan yang sudah terjalin sejak lama.
Mbah Podho, juru kunci makam Mbah Sa’id Anom, sering kali mengingatkan warga tentang makna sejati nyadran. Menurutnya, nyadran bukan hanya ritual tahunan, tetapi juga sarana memperkuat ikatan manusia dengan leluhur dan alam. “Tujuannya supaya diberi kesarasan, menopo kemawon lancar, nandur-nandur nggih subur,” ujarnya dengan lembut, yang artinya agar segala urusan berjalan lancar dan hasil bumi tetap subur.
Kini, Desa Sonoageng yang terdiri atas lima dusun yakni Sonoageng, Banyurip, Sumber, Gading, dan Waung. Kelimanya masih menjaga tradisi itu dengan penuh kebanggaan. Di tengah kemajuan zaman, nyadran dan tumpengan tetap menjadi jembatan antara masa lalu dan masa kini, mengingatkan warga bahwa kesejahteraan tidak datang hanya dari kerja keras, tetapi juga dari rasa hormat dan syukur kepada alam serta leluhur.
Melalui kisah dan ritual ini, Desa Sonoageng mengajarkan sebuah pesan yang dalam: bahwa kehidupan manusia akan selalu kuat jika berakar pada kebersamaan, kesederhanaan, dan rasa terima kasih. Tumpeng yang dihidangkan setiap nyadran menjadi simbol kearifan lokal yang abadi, mengingatkan kita semua untuk menjaga keseimbangan antara dunia lahir dan batin. Di bawah teduhnya langit Jawa Timur, semangat Mbah Sa’id Anom seakan masih bernafas di setiap doa dan aroma nasi tumpeng yang mengepul, membawa pesan abadi tentang keselarasan antara manusia, alam, dan Tuhan.